Istilah budaya keselamatan
(safety culture) menjadi populer setelah disebut di dalam laporan investigasi
kecelakaan pembangkit tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina (IAEA, 1986) yang
dibuat oleh International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG). Badan tenaga
atom internasional, IAEA (International Atomic Energy Agency) memperkenalkan
konsep yang menjelaskan kesalahan organisasi dan pelanggaran operator yang
menjadi penyebab bencana tersebut.
Sejak saat
itu, ‘buruknya budaya keselamatan’ jadi sering teridentifikasi di berbagai
kecelakaan berskala besar di beberapa industri, seperti kebakaran stasiun bawah
tanah King’s Cross (Fennell, 1998), tenggelamnya kapal feri Herald of Free
Enterprise (Sheen, 1987), kecelakaan kereta penumpang di simpangan Clapham
(Hidden, 1989), bencana pesawat ulang-aling Challenger (Rogers, 1986) dan pesawat
ulang-aling Columbia (Gehman, 2003), tabrakan pesawat udara Überlingen
(Ruitenberg, 2005), dan kecelakaan di pengilangan minyak BP (Baker et al.,
2005).
Budaya
keselamatan menjadi bahan yang menarik para peneliti di berbagai industri
berisiko tinggi semisal minyak dan gas (Flin et al., 1998), (Cox and Cox,
1991), (Mineral Concil of Australia, 1999), transportasi udara (Gordon et al.,
2006), (Ek, 2006), (Wiegmann et al. 2003), (Patankar et al., 2005), juga di
bidang keselamatan nuklir (Ostrom et al., 1993), (Meshkati, 1997), (Carroll,
1998), dan baru-baru ini di ranah transportasi kereta api dan kesehatan.
Dalam banyak literatur,
ada berbagai macam penjabaran karakteristik budaya keselamatan. James Reason
(1997), salah satu peneliti utama ilmu keselamatan, profesor di Universitas
Manchester menerangkan bahwa budaya keselamatan terdiri dari empat aspek:
- Budaya pelaporan (reporting culture), yang mendorong pekerja untuk membuka informasi mengenai semua bahaya yang mereka temui
- Budaya adil (just culture), yang membuat pekerja bertanggungjawab atas pelanggaran peraturan yang disengaja, namun mendorong dan memberikan penghargaan bagi mereka yang menyediakan informasi penting terkait keselamatan
- Budaya yang fleksibel (flexible culture), dimana pekerja dapat secara efektif beradaptasi atas perubahan dan memberikan respon yang lebih cepat dan halus terhadap kejadian yang tidak diinginkan
- Budaya belajar (learning culture), yang mau berubah karena adanya indikasi keselamatan dan bahaya yang ditemukan ketika melakukan penilaian, audit, dan analisa kecelakaan.
Pada artikel
kali ini, mari kita ulas lebih jauh mengenai budaya adil dan budaya pelaporan.
Just culture
(budaya yang adil) adalah budaya yang memberikan batasan jelas antara kinerja
yang dapat diterima (acceptable) dengan kinerja yang tidak dapat diterima
(unacceptable). Atau bisa disebut juga budaya saling percaya, belajar, dan
akuntabilitas.
Sebelum
melangkah lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa kegagalan (dan
juga kesuksesan) merupakan kombinasi hasil dari beberapa faktor yang saling
terkait –yang kesemuanya harus ada secara memadai.
Dengan
tantangan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity) yang
dihadapi fungsi operasional sehari-hari, beberapa orang dengan mudah
menyalahkan pekerja atau manusia ketika mengalami kegagalan, sedang beberapa
orang lainnya menyalahkan sistem kerja atau organisasi.
Just culture
hadir untuk memberikan keseimbangan dari kedua hal tersebut.
Euro Control,
memberikan tambahan penjelasan mengenai just culture, yaitu ketika seorang
tidak dihukum karena aksi, ketiadaan aksi (omission) atau keputusan yang mereka
ambil, yang telah sesuai dengan tingkat pengalaman dan pelatihan mereka, namun
hal itu tidak menoleransi kelalaian, pelanggaran yang disengaja, dan tindakan
perusakan.
Harapannya,
dengan adanya just culture, pekerja akan semakin banyak melaporkan kejadian,
baik berupa kecelakaan, near miss, kondisi berisiko, ataupun hal lain yang bisa
mengakibatkan gangguan operasi.
Namun, untuk
dapat meningkatkan pelaporan, perlu lebih dahulu ditingkatkan kemudahan
mengakses pelaporan dan mengurangi kecemasan terkait pelaporan.
Cara
mengurangi kecemasan pelaporan adalah dengan memberikan kepastian kepada
pekerja bahwa laporan mereka ditindaklanjuti, terjamin kerahasiaannya, tidak
membahayakan karir mereka sendiri ataupun rekan kerja lainnya.
Dan untuk
membuat pelaporan terus berlanjut, perlu ada umpan balik, pelibatan pelapor,
dan bukti adanya perubahan.
Tiga kriteria
untuk membuat pelaporan sukses adalah voluntary (suka rela), karena para
pekerja adalah personil ahli di bidangnya, mereka mengetahui apa yang perlu
atau tidak perlu dilaporkan; non-punitive (tidak menghukum), kita belajar lebih
banyak dari kesalahan, dengan memberikan hukuman atau sanksi (memecat pekerja,
contohnya) hanya akan menghilangkan pelajaran tersebut; protected (dilindungi),
terjamin merahasiaannya dan tidak anonim untuk memudahkan klasifikasi pelaporan
dan tindak lanjut.
Menurut
Sidney Dekker, ada dua pendekatan just culture: retributive dan restorative.
Retributive
just culture menekankan pemberian sanksi secara proporsional jika ada kinerja
yang tidak dapat diterima.
Tigas
pertanyaan yang biasa muncul dengan pendekatan ini adalah: peraturan apa yang
dilanggar, seberapa berat pelanggarannya, dan bagaimana konsekuensi bagi si
pelanggar.
Untuk
membantu pendekatan ini, secara umum ada tigas klasifikasi pengelompokan (shade
of retribution) atas tindakan yang tidak dapat diterima (unacceptable
performance): negligence (kelalaian), at-risk behavior (perilaku berisiko), dan
honest mistake (kesalahan tidak disengaja).
Ringan
beratnya konsekuensi bagi si pelanggar akan berbeda, tergantung tingkat
pelanggarannya. Semakin ke ujung kiri, semakin berat sanksinya.
Namun,
pendekatan ini tidak mudah dan memiliki banyak tantangan, karena ada banyak sekali
hal subyektif yang dapat diperdebatkan. Misalnya, negligence bukanlah istilah
yang dipergunakan dalam ilmu human performance tapi dipergunakan di ranah hukum/legal,
kesamaan batasan mengenai standar normal, definisi arti di bawah kinerja,
perilaku yang masuk akal, memadai, dst.
Untuk
memudahkan aplikasinya, beberapa organisasi mempergunakan decision tree atau
flow chart untuk menentukan jenis dan besar atau kecilnya sanksi, yang
merupakan pengembangan culpability decision tree dari James Reason, 1997.
Yang menarik
dari grafik tersebut adalah dimulai dengan ‘anda bersalah’ sampai tidak
terbukti bahwa tindakan yang ada merupakan kesalahan sistem, dengan
mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang tersedia.
Apakah hal
tersebut akan memicu pelaporan yang baik? Sepertinya tidak.
Apakah hal
tersebut akan memberikan keadilan yang diharapkan atau pembelajaran setelah
kejadian? Sepertinya sulit.
Dalam
praktiknya, pendekatan ini mudah menyalahkan pekerja, tidak memberikan pelajaran
berarti; hanya mengeluarkan pelaku yang berada di ‘permukaan’ atau sebagai
gejala/symptom saja; dan tidak menunjukkan pemahaman mendalam akan kondisi
sistemik penyebab kejadian.
Sebuah survei
yang dilakukan pada 2006 dengan 1984 koresponden di Rumah Sakit menunjukkan
kesimpulan bahwa dengan pendekatan retributive just culture, orang yang
memiliki kekuasaan yang besar, akan melihat hal itu sudah adil “just culture”,
tetapi orang yang memiliki kekuasaan lebih kecil, hanya melihat itu sebagai
alat untuk menghukum.
Akibatnya,
just culture yang digadang-gadang sebagai program perbaikan berkelanjutan, hanya
jadi program untuk menyalahkan pekerja, sehingga akhirnya akan menurunkan
tingkat pelaporan.
Jika ingin
membuat budaya pembelajaran dan adil, retributive just culture mungkin
sebaiknya tidak dipergunakan. Namun, jika tetap memaksa mempergunakan pendekatan
ini, dibutuhkan tiga syarat: wasit yang independen (independent judge) yang
tidak memiliki konflik kepentingan ketika mempergunakan decision tree tersebut;
pengetahuan detail yang luas (knowledge of messy details); dan peluang untuk
banding atau pembelaan bagi pekerja yang mendapat hukuman (opportunity for
appeal).
Selain
pendekatan di atas, ada restorative just culture, yaitu ketika semua pihak yang
terlibat memiliki kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah
dipengaruhi oleh ketidakadilan dan memutuskan apa yang harus mereka lakukan
untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.
Tiga
pertanyaan yang biasanya dipergunakan restorative just culture adalah: siapa
yang telah cedera, apa yang mereka butuhkan, kewajiban siapa yang akan memenuhi
kebutuhan tersebut.
Kita buat
contoh perbandingan. Seorang pekerja menyatakan bahwa ia membuat error ketika
melakukan pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian dan membuat risiko
keselamatan. Jika mempergunakan retributive just culture, perilaku penyebab kejadian
tersebut akan dimasukkan ke decision tree flow chart dan 3 pertanyaan untuknya
yaitu: apa yang dilanggar, seberapa berat pelanggarannya, konsekuensi apa yang
akan ia dapatkan –dengan kemungkinan akan dipecat.
Tapi, jika
mempergunakan restorative just culture, dengan dirinya suka rela mau maju membicarakan
kesalahannya dan direkam dalam video, menjelaskan situasi yang mengarahkan dia
ke dalam jebakan error, menjelaskan akibat tindakan yang ia lakukan, menunjukkan
perasaan tanggung jawab, penyesalan, dan memberikan pembelajaran pada rekan
kerja.
Bagi pekerja,
hal ini memberitahu akuntabilitasnya (honest disclosure, giving of an account);
membayar hutangnya pada perusahaan dan rekan kerja, dengan berbagi pelajaran;
menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab; akuntabilitas yang menatap masa
depan (forward-looking accountability); dan menjelaskan hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Bagi perusahaan,
hal itu tidak melepas pekerja dari tanggung jawab. Pekerja akan belajar dari hal
tersebut. Terbangun kepercayaan berdasarkan kejujuran satu sama lain; teridentifikasi
kondisi sistemik yang membuat jebakan error bagi dirinya dan potensi menjebak
juga bagi orang lain. Sedang, jika dihukum atau dipecat, maka pelajaran akan
hilang, dan menurunkan motivasi pekerja lainnya;
Dengan
demikian, retributive just culture berbeda dengan restorative just culture.
Retributive just culture melihat akuntabilitas ke belakang atau masa lalu (backward-looking
accountability), mencari tahu siapa yang bertanggungjawab, dan apa konsekuensi
yang akan diberikan kepada pekerja yang berbuat error. Sedang restorative just
culture melihat akuntabilitas ke masa depan (forward-looking accountability),
mencari tahu apa yang bertanggungjawab, dan apa yang harus dilakukan sekarang
untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi.
Apa yang
bertanggungjawab pada restorative just culture bisa berupa batasan-batasan
operasional yang ada, konflik tujuan (goal conflict), kesalahan desain, atau
isu pada organisasi.
Retributive
just culture mempertemukan kegagalan atau luka (dampak kecelakaan) dengan luka baru
(pemecatan, sakit hati), sedangkan restorative just culture mempertemukan luka
dengan obat/penyembuhan.
---000---
Penyusun:
Syamsul
Arifin, SKM. MKKK.
Praktisi K3LH
www.syamsularifin.org
Referensi:
EUROCONTROL. Safety Culture in Air Traffic Management,
A White Paper. December 2008
Dekker, Sidney. Just Culture, Balancing Safety and
Accountability. 2007. Inggris
Dekker, Sidney. Just Culture, Restoring Trust and
Accountability in Your Organization. 2016. Inggris
Dekker, Sidney. “Just Culture short course 1 - 4”,
Youtube. 1 Des 2015. Web

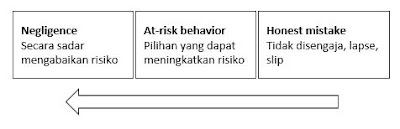


Tidak ada komentar:
Posting Komentar